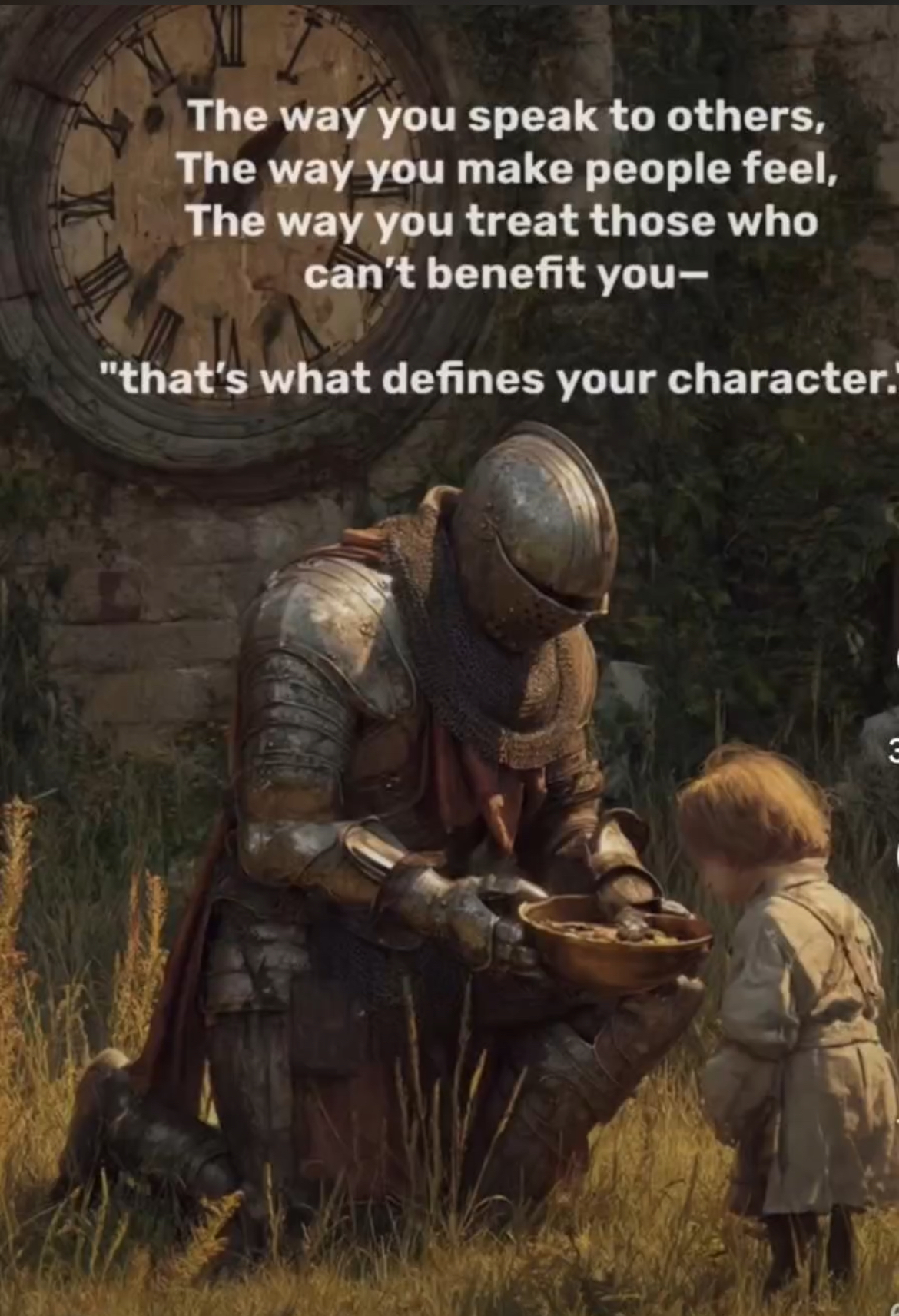Kemerdekaan Palestina sebagai Ujian Kemanusiaan Global
Di tengah hiruk-pikuk Konferensi Keamanan Munich ke-62 yang membicarakan keretakan hubungan transatlantik, krisis kepercayaan antara Eropa dan Amerika Serikat, serta kemungkinan pengembangan pencegahan nuklir Eropa, satu pertanyaan fundamental sering terlupakan: bagaimana dengan nasib Palestina? Ketika para pemimpin dunia sibuk menghitung ulang kepentingan strategis mereka, membentuk kembali aliansi, dan mendesain ulang arsitektur keamanan global, rakyat Palestina terus menunggu, terus berharap, dan terus mati. Puluhan ribu warga sipil telah tewas di Gaza sejak eskalasi terbaru, rumah sakit hancur, sekolah rata dengan tanah, dan generasi baru tumbuh di tengah puing-puing dan trauma. Namun, kemerdekaan Palestina masih tertahan di ruang-ruang veto Dewan Keamanan PBB, masih tersandera oleh kalkulasi politik negara-negara besar, dan masih menjadi korban dari apa yang oleh para analis disebut sebagai “krisis tatanan liberal berbasis aturan.”
Pembelaan terhadap kemerdekaan Palestina bukanlah sekadar soal solidaritas moral atau sentimen keagamaan. Ia adalah ujian terbesar bagi kredibilitas sistem internasional yang mengklaim menjunjung tinggi hukum internasional, hak asasi manusia, dan prinsip penentuan nasib sendiri. Ketika negara-negara Barat dengan lantang membela Ukraina atas nama kedaulatan territorial, namun diam atau bahkan memasok senjata ketika Palestina mengalami pendudukan dan kolonisasi sistematis selama lebih dari tujuh dekade, maka yang terungkap adalah standar ganda yang menghancurkan legitimasi tatanan global itu sendiri. Friedrich Merz, Kanselir Jerman, mungkin benar ketika mengatakan bahwa “jurang pemisah yang dalam” telah terbuka antara Eropa dan Amerika. Namun jurang yang lebih dalam lagi adalah antara retorika negara-negara maju tentang hak asasi manusia dan praktik nyata mereka dalam membiarkan, bahkan mendukung, penindasan terhadap rakyat Palestina.
Dalam lanskap geopolitik yang semakin transaksional dan didominasi logika keamanan, pembelaan terhadap kemerdekaan Palestina membutuhkan pendekatan baru. Bukan pendekatan yang mengorbankan prinsip, tetapi pendekatan yang lebih cerdas dalam membaca peta kekuasaan, lebih strategis dalam memilih bahasa advokasi, dan lebih berani dalam memasuki ruang-ruang yang selama ini dianggap tidak ramah. Artikel ini berargumen bahwa untuk mencapai kemerdekaan, perjuangan Palestina harus mampu menerjemahkan tuntutan moralnya ke dalam bahasa kepentingan strategis, keamanan, dan stabilitas global—bahasa yang dipahami oleh mereka yang memegang kendali kebijakan di ibu kota-ibu kota dunia.
Mengapa Solidaritas Global Belum Cukup
Sebelum merumuskan strategi baru, kita harus jujur mengakui realitas pahit: gerakan solidaritas Palestina telah mencapai visibilitas yang luar biasa, namun visibilitas itu belum berubah menjadi pengaruh politik yang nyata. Di seluruh dunia, jutaan orang turun ke jalan membela Palestina. Tagar #FreePalestine membanjiri media sosial. Mahasiswa di universitas-universitas Barat mendirikan perkemahan protes. Boikot terhadap produk-produk yang terkait dengan pendudukan mendapatkan momentum baru. Di tingkat internasional, Mahkamah Internasional (ICJ) dan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mulai menyelidiki kejahatan perang di wilayah Palestina. Ini adalah pencapaian yang tidak bisa diremehkan.
Namun di saat yang sama, senjata terus mengalir dari Amerika Serikat dan Jerman ke Israel. Perlindungan diplomatik di Dewan Keamanan PBB terus diberikan melalui veto yang menghalangi resolusi gencatan senjata. Di berbagai negara Barat, demonstrasi pro-Palestina justru dibatasi, dilarang, atau dibingkai sebagai ancaman keamanan nasional. Di Jerman, otoritas setempat melarang atau membatasi secara ketat demonstrasi dengan alasan antisemitisme—sebuah tuduhan yang sering digunakan untuk membungkam kritik terhadap kebijakan Israel. Di Amerika Serikat, perkemahan mahasiswa dibubarkan paksa oleh polisi, dan badan legislatif negara bagian menghukum institusi yang dianggap mentoleransi kampanye boikot. Di Inggris, protes besar-besaran dibingkai terutama melalui bahasa ekstremisme dan ketertiban umum.
Mengapa ini terjadi? Analisis wacana kritis terhadap respons negara-negara Barat mengungkapkan pola yang konsisten: perdebatan dengan sengaja dialihkan dari ranah hukum internasional ke ranah keamanan domestik. Dengan membingkai protes sebagai ancaman ketertiban umum, ekstremisme, atau bahkan antisemitisme, pemerintah menghindari diskusi substantif tentang pendudukan, apartheid, kolonisasi, atau kejahatan perang. Mereka memindahkan medan pertempuran ke wilayah di mana mereka merasa paling percaya diri: wilayah di mana mereka bisa mengklaim melindungi keamanan nasional, bukan wilayah di mana mereka harus mempertanggungjawabkan pelanggaran hukum internasional oleh sekutu mereka.
Lebih fundamental lagi, advokasi Palestina selama ini terlalu bergantung pada register linguistik yang hanya beresonansi di kalangan progresif: bahasa antikolonial, hak asasi manusia, solidaritas moral, dan keadilan historis. Bahasa-bahasa ini, meskipun benar secara normatif dan penting untuk memelihara solidaritas akar rumput, gagal menembus ruang-ruang kekuasaan yang didominasi oleh logika keamanan, kepentingan strategis, dan kalkulasi transaksional. Di ruang-ruang seperti komite keamanan nasional, forum kebijakan luar negeri konservatif, atau ruang sidang parlemen yang didominasi partai kanan, bahasa yang didengar bukanlah bahasa keadilan, melainkan bahasa stabilitas, kepentingan nasional, dan keseimbangan kekuasaan.
Akibatnya, isu Palestina dengan mudah dicap sebagai “ideologis,” “ekstremis,” atau “bukan kepentingan nasional kita.” Ia menjadi isu yang hanya milik kalangan tertentu, bukan isu universal tentang hukum dan ketertiban internasional. Dan selama ia dipersepsikan demikian, negara-negara besar akan merasa tidak memiliki kepentingan untuk mengubah kebijakan mereka.
Dari Bahasa Moral ke Bahasa Kekuasaan
Di sinilah konsep “penerjemahan politik” (political translation) menjadi relevan dan mendesak. Jika kebijakan internasional dibentuk di ruang-ruang yang didominasi oleh pemikiran keamanan dan kekuasaan konservatif, maka advokasi untuk kemerdekaan Palestina harus menjangkau ruang-ruang itu dengan bahasa yang dapat dipahami. Ini bukan berarti meninggalkan prinsip atau mengencerkan tuntutan. Ini berarti menemukan kendaraan bahasa yang berbeda untuk membawa muatan prinsip yang sama ke ruang yang berbeda. Ini adalah soal strategi komunikasi, soal kecerdasan dalam membaca audiens, dan soal keberanian untuk memasuki ruang yang tidak nyaman.
Apa artinya ini secara konkret? Pertama, tuntutan “Hentikan Pendudukan” dapat dan harus diterjemahkan ke dalam bahasa keamanan: “Pendudukan yang tak berkesudahan merusak keamanan jangka panjang Israel sendiri dengan menciptakan ketidakstabilan permanen, melahirkan generasi baru militan, dan menghancurkan prospek solusi dua negara yang selama ini menjadi fondasi kebijakan Barat.” Argumen ini berbicara langsung pada keprihatinan kaum realis tentang stabilitas dan keamanan. Ia tidak meminta mereka untuk peduli pada keadilan bagi Palestina; ia meminta mereka untuk peduli pada keamanan Israel dan kawasan, yang justru terancam oleh kelanjutan pendudukan.
Kedua, ketidakadilan terhadap Palestina harus diterjemahkan ke dalam bahasa kredibilitas dan konsistensi: “Penerapan hukum internasional yang selektif, di mana Ukraina dibela mati-matian sementara Palestina diabaikan, merusak kredibilitas Barat secara fatal. Jika hukum internasional hanya berlaku ketika nyaman bagi kepentingan kita, maka kita kehilangan hak moral untuk menuntut kepatuhan dari negara lain—baik di Eropa Timur, Asia, maupun kawasan lainnya.” Argumen ini menyentuh kepentingan negara-negara Barat dalam mempertahankan tatanan global yang mereka anggap menguntungkan. Ia menunjukkan bahwa inkonsistensi dalam membela Palestina pada akhirnya merugikan kepentingan strategis mereka sendiri.
Ketiga, impunitas yang dinikmati Israel harus diterjemahkan ke dalam bahasa deterens dan tatanan global: “Kekebalan hukum bagi satu sekutu mengikis efek jera (deterrence) secara global, karena melemahkan norma-norma yang seharusnya melindungi semua negara. Ketika pelanggaran hukum internasional tidak mendapat sanksi, pesan yang dikirimkan adalah bahwa kekuatan, bukan aturan, yang menentukan. Ini adalah preseden berbahaya yang pada akhirnya akan digunakan oleh aktor-aktor lain di berbagai belahan dunia.” Argumen ini membingkai isu Palestina bukan sebagai kasus khusus, tetapi sebagai ujian bagi sistem internasional secara keseluruhan.
Keempat, perjuangan kemerdekaan Palestina dapat diterjemahkan ke dalam bahasa kepentingan ekonomi dan stabilitas kawasan: “Konflik yang berkepanjangan di Palestina adalah sumber utama radikalisasi di kawasan Timur Tengah dan sekitarnya. Ia menjadi alat rekrutmen bagi kelompok-kelompok ekstremis, mengganggu stabilitas negara-negara tetangga, dan menciptakan gelombang pengungsi yang membebani ekonomi regional dan global. Penyelesaian konflik ini justru akan membuka peluang kerja sama ekonomi, integrasi kawasan, dan pembangunan yang selama ini terhambat.” Argumen ini berbicara pada kepentingan pragmatis negara-negara yang ingin mengurangi ancaman terorisme, mengelola migrasi, dan membuka pasar baru.
Penting untuk ditekankan lagi: penerjemahan ini bukan berarti mengubah tujuan akhir kemerdekaan Palestina. Tujuan itu tetap tidak tergoyahkan: sebuah negara Palestina yang merdeka dan berdaulat, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya, hak kembali bagi pengungsi sesuai resolusi PBB, dan pengakhiran pendudukan di semua wilayah Palestina. Yang berubah adalah bahasa yang digunakan untuk memperjuangkannya di forum-forum di mana bahasa keadilan saja tidak cukup.
Ketika Gerakan Perlawanan Berhasil Menjangkau Musuh
Sejarah perlawanan di berbagai belahan dunia menawarkan pelajaran berharga. Kongres Nasional Afrika (ANC) di bawah kepemimpinan Nelson Mandela tidak membatasi perjuangannya hanya pada kalangan progresif dan anti-apartheid. Mereka secara aktif melakukan diplomasi dengan pemerintahan Barat yang konservatif, dengan pemimpin bisnis yang selama ini diuntungkan oleh rezim apartheid, dan bahkan dengan elemen-elemen dalam pemerintahan Afrika Selatan sendiri. Mereka menerjemahkan tuntutan kebebasan ke dalam bahasa stabilitas ekonomi, kepentingan bisnis, dan masa depan kawasan. Mereka tidak pernah mengkompromikan tujuan akhir penghapusan apartheid, tetapi mereka cerdas dalam memilih bahasa dan strategi untuk mencapai tujuan itu.
Hal yang sama dilakukan oleh gerakan republikan Irlandia (Sinn Féin) dalam perjuangan mereka menyatukan Irlandia Utara dengan Republik Irlandia. Setelah bertahun-tahun konflik bersenjata, mereka duduk bernegosiasi dengan pemerintahan konservatif Inggris yang sangat menentang tujuan mereka. Mereka memasuki ruang-ruang yang sebelumnya tidak mungkin mereka masuki. Mereka berbicara dalam bahasa yang dapat didengar oleh lawan. Hasilnya adalah Perjanjian Jumat Agung (Good Friday Agreement) yang membuka jalan bagi proses damai dan power-sharing, meskipun tujuan akhir penyatuan Irlandia belum tercapai.
Dalam kedua kasus ini, keterlibatan dengan pihak yang memusuhi tidak pernah dianggap sebagai pengkhianatan atau kompromi moral. Ia dipahami sebagai kebutuhan strategis: bahwa perubahan politik yang nyata membutuhkan akses ke pusat-pusat kekuasaan, betapapun tidak ramahnya pusat kekuasaan itu. Politik adalah seni kemungkinan, dan kemungkinan sering terbuka justru ketika kita berani memasuki ruang yang paling tidak nyaman.
Perjuangan Palestina memiliki legitimasi moral yang tidak kalah kuat dari kedua gerakan itu. Bahkan, dalam banyak hal, ia lebih kuat karena didasarkan pada hukum internasional yang eksplisit, resolusi-resolusi PBB yang tak terhitung jumlahnya, dan opini Mahkamah Internasional yang mengakui hak-hak rakyat Palestina. Namun legitimasi moral ini harus dilengkapi dengan kecerdasan strategis. Tanpa itu, ia akan terus terperangkap dalam ruang gema, semakin keras bersuara tetapi semakin tidak didengar oleh mereka yang memegang kendali.
Membuka Celah di Kalangan yang Selama Ini Memusuhi
Salah satu aspek paling penting dari strategi penerjemahan politik adalah pengakuan bahwa “kanan” tidaklah monolitik. Istilah ini menyembunyikan keragaman yang sangat besar: ada nasionalis yang peduli pada kedaulatan dan integritas territorial; ada libertarian yang skeptis terhadap intervensi asing dan menentang pemborosan anggaran militer untuk petualangan di luar negeri; ada konservatif tradisional yang khawatir tentang penyalahgunaan kekuasaan eksekutif dan erosi checks and balances; ada realis yang memandang dunia melalui lensa kepentingan nasional dan keseimbangan kekuasaan, bukan melalui lensa ideologis.
Masing-masing kelompok ini, jika didekati dengan argumen yang tepat, dapat menjadi celah masuk bagi advokasi Palestina. Nasionalis dapat diajak bicara tentang bagaimana pendudukan Israel melanggar prinsip kedaulatan dan hak menentukan nasib sendiri yang seharusnya menjadi milik semua bangsa. Libertarian dapat diajak bicara tentang bagaimana bantuan militer AS yang tak terbatas ke Israel adalah pemborosan uang pembayar pajak yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan domestik. Konservatif tradisional dapat diajak bicara tentang bagaimana penggunaan kekuasaan eksekutif yang tidak terkendali dalam mendukung sekutu, tanpa pengawasan kongres yang memadai, menciptakan preseden berbahaya. Kaum realis dapat diajak bicara tentang bagaimana dukungan tanpa syarat kepada Israel justru merusak kepentingan jangka panjang AS di kawasan Arab dan Muslim, menciptakan ketidakstabilan yang pada akhirnya merugikan semua pihak.
Tentu, tidak semua dari mereka akan terpengaruh. Beberapa mungkin tetap tidak tergoyahkan karena komitmen ideologis atau keagamaan yang dalam. Tetapi dengan tidak mencoba menjangkau mereka sama sekali, dengan menganggap mereka “secara inheren tidak bisa dijangkau,” kita secara tidak sadar menyerahkan medan perang kebijakan sepenuhnya kepada narasi paling ekstrem yang mendominasi diskusi internal mereka. Keheningan kita adalah persetujuan kita terhadap status quo.
Di sinilah pentingnya membangun infrastruktur advokasi yang memadai: lembaga riset yang menghasilkan policy brief untuk legislator konservatif, forum diskusi yang mempertemukan aktivis Palestina dengan pemikir dari kalangan kanan, publikasi opini di media-media arus utama yang selama ini menjadi rujukan pengambil kebijakan, dan pelatihan bagi juru bicara yang mampu berdebat di ruang komite keamanan dan parlemen. Ini adalah investasi jangka panjang yang mungkin tidak membuahkan hasil segera, tetapi tanpanya, perjuangan Palestina akan terus terperangkap dalam siklus protes yang semakin keras namun semakin tidak efektif.
Peran Kita Menjadi Jembatan dan Penggerak
Di tengah lanskap geopolitik yang semakin multipolar dan transaksional, Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, sejarah perjuangan dekolonisasi yang kuat, dan tradisi diplomasi bebas aktif, memiliki peran strategis yang unik dalam pembelaan terhadap kemerdekaan Palestina. Peran ini tidak boleh terbatas pada retorika dukungan moral di forum-forum multilateral, tetapi harus diterjemahkan ke dalam tindakan diplomasi yang cerdas dan terukur.
Pertama, Indonesia dapat menjadi “penerjemah” antara tuntutan Palestina dan bahasa kepentingan strategis yang dipahami oleh negara-negara besar. Dengan posisinya yang tidak memihak dalam persaingan AS-Tiongkok, dengan hubungan baiknya dengan dunia Islam dan Barat, serta dengan pengalamannya sebagai negara yang pernah berjuang melawan kolonialisme, Indonesia memiliki kredibilitas untuk menjelaskan kepada negara-negara maju bahwa penyelesaian konflik Palestina justru sejalan dengan kepentingan jangka panjang mereka sendiri—dalam hal stabilitas kawasan, kontra-terorisme, manajemen migrasi, dan pembukaan pasar baru.
Kedua, Indonesia dapat memimpin upaya membangun koalisi kekuatan menengah (middle power coalition) untuk Palestina. Negara-negara seperti Brasil, India, Afrika Selatan, Turki, dan Malaysia memiliki kepentingan bersama dalam memperkuat hukum internasional dan multilateralisme. Jika bersatu, mereka dapat menjadi kekuatan penyeimbang yang signifikan di forum-forum seperti PBB, Gerakan Non-Blok, dan OKI. Mereka dapat menginisiasi resolusi-resolusi kreatif yang tidak mudah diveto, menggunakan mekanisme “Uniting for Peace” di Majelis Umum PBB, dan memberikan tekanan diplomatik kolektif melalui berbagai saluran.
Ketiga, Indonesia perlu mengintegrasikan isu Palestina ke dalam kerangka kepentingan nasional yang lebih luas, bukan sekadar sebagai isu solidaritas. Ini berarti menjelaskan kepada publik domestik dan internasional bahwa stabilitas di Palestina terkait langsung dengan stabilitas kawasan Timur Tengah yang menjadi sumber energi dunia, bahwa radikalisasi yang dipicu oleh ketidakadilan di Palestina pada akhirnya dapat berdampak pada keamanan Indonesia sendiri, dan bahwa perdamaian di Palestina akan membuka peluang ekonomi dan investasi yang dapat dinikmati oleh banyak negara, termasuk Indonesia.
Keempat, Indonesia dapat menjadi contoh bagaimana melakukan advokasi Palestina di ruang-ruang konservatif. Dengan mayoritas penduduknya yang religius namun moderat, dengan tradisi toleransi dan kerukunan umat beragama, Indonesia memiliki posisi unik untuk berbicara tentang Palestina tanpa terjebak dalam polarisasi “Barat versus Islam.” Diplomasi Indonesia dapat menunjukkan bahwa membela Palestina bukanlah anti-Semitisme, bukan pula anti-Barat, melainkan pembelaan terhadap prinsip universal hukum internasional dan hak asasi manusia.
Menjawab Kekhawatiran tentang Strategi Baru
Setiap strategi baru akan menghadapi keberatan, dan penting untuk menjawabnya secara jujur. Keberatan paling umum terhadap pendekatan penerjemahan politik adalah bahwa ia berisiko “menormalisasi” wacana rasis atau konservatif, atau bahwa ia mengkompromikan kemurnian moral perjuangan. Kekhawatiran ini perlu direspon dengan serius.
Pertama, penting untuk membedakan antara berbicara dengan dan setuju dengan. Berbicara dengan aktor-aktor konservatif, memasuki ruang yang didominasi oleh pemikiran keamanan, dan menggunakan bahasa yang mereka pahami, bukan berarti menyetujui seluruh kerangka berpikir mereka. Ini adalah pengakuan pragmatis bahwa perubahan kebijakan membutuhkan dialog dengan mereka yang memegang kekuasaan, bukan hanya dengan mereka yang sudah sepaham. Seperti yang diajarkan oleh pengalaman ANC dan Sinn Féin, keterlibatan tidak sama dengan dukungan.
Kedua, risiko terbesar sebenarnya bukanlah kooptasi, melainkan ketidakrelevanan. Dengan tetap berada di ruang gema, melindungi kemurnian moral tetapi gagal mempengaruhi kebijakan, gerakan solidaritas Palestina secara tidak sadar membiarkan medan pertempuran kebijakan dikuasai sepenuhnya oleh narasi yang merugikan. Setiap tahun kita tidak hadir di ruang-ruang itu, narasi yang menggambarkan Palestina sebagai ancaman keamanan, bukan korban ketidakadilan, semakin menguat. Setiap tahun kita hanya berbicara di kampus dan jalanan, sementara kebijakan dirumuskan di ruang komite dan parlemen, kita semakin kehilangan pengaruh.
Ketiga, penerjemahan politik justru membutuhkan kepercayaan diri yang besar pada keadilan perjuangan. Jika kita benar-benar yakin bahwa tuntutan kemerdekaan Palestina didasarkan pada prinsip universal yang tak terbantahkan—hukum internasional, hak menentukan nasib sendiri, perlawanan terhadap pendudukan—maka kita seharusnya tidak takut untuk mengartikulasikannya di forum mana pun, dalam bahasa apa pun, di hadapan audiens mana pun. Keyakinan sejati tidak membutuhkan ruang aman; ia justru berkembang ketika diuji di ruang yang paling tidak bersahabat.
Keempat, penting untuk memiliki batasan yang jelas tentang apa yang tidak dapat dikompromikan. Penerjemahan politik bukan berarti menerima legitimasi pendudukan, bukan berarti mengakui “hak Israel sebagai negara Yahudi” yang menafikan hak kembali pengungsi, bukan berarti mengabaikan kejahatan perang yang dilakukan. Bahasa boleh berubah, tetapi inti tuntutan tetap: pengakhiran pendudukan, kemerdekaan Palestina, hak kembali, dan Yerusalem Timur sebagai ibu kota. Ini adalah garis merah yang tidak bisa dilanggar. Penerjemahan adalah tentang strategi komunikasi, bukan tentang mengubah substansi perjuangan.
Menyatukan Advokasi Akar Rumput dan Diplomasi Elit
Penerjemahan politik tidak boleh dipahami sebagai pengganti advokasi akar rumput, melainkan sebagai pelengkapnya. Gerakan solidaritas Palestina membutuhkan strategi terpadu yang bekerja di dua level secara simultan.
Di level akar rumput, mobilisasi massa, pendidikan publik, dan kampanye boikot tetap penting. Mereka membangun tekanan publik, menciptakan kesadaran, dan menunjukkan bahwa ada konstituensi yang peduli. Mereka juga memberikan legitimasi dan dukungan bagi mereka yang berjuang di level elit. Tanpa gerakan akar rumput yang kuat, diplomasi elit akan kehilangan energi dan mandatnya.
Di level elit, penerjemahan politik dan diplomasi strategis bekerja untuk menerjemahkan tekanan publik menjadi perubahan kebijakan. Mereka membangun hubungan dengan para pengambil keputusan, menyusun argumen yang relevan dengan kepentingan mereka, dan membuka celah di kalangan yang selama ini memusuhi. Mereka adalah jembatan antara protes di jalanan dan keputusan di ruang kekuasaan.
Kedua level ini harus berjalan beriringan, saling memperkuat. Gerakan akar rumput menciptakan urgensi dan visibilitas; diplomasi elit menerjemahkannya menjadi leverage dan pengaruh. Tanpa yang pertama, yang kedua kehilangan energi. Tanpa yang kedua, yang pertama kehilangan arah dan efektivitas.
Kemerdekaan Palestina sebagai Tanggung Jawab Bersama
Pada akhirnya, pembelaan terhadap kemerdekaan Palestina adalah tanggung jawab kita semua—bukan hanya karena ikatan moral atau keagamaan, tetapi karena ia adalah ujian bagi kemanusiaan kita bersama. Jika dunia bisa membiarkan pendudukan, kolonisasi, dan kejahatan perang berlangsung selama lebih dari tujuh dekade terhadap satu bangsa, maka apa artinya hukum internasional? Jika negara-negara besar bisa menerapkan standar ganda dengan begitu terang-terangan—membela Ukraina dengan gigih namun mengabaikan Palestina—lalu apa artinya keadilan? Jika sistem multilateral yang dibangun dengan susah payah setelah Perang Dunia II bisa lumpuh oleh veto dan kepentingan sempit, lalu apa gunanya institusi internasional?
Perjuangan kemerdekaan Palestina adalah cermin bagi dunia. Ia merefleksikan kemunafikan, inkonsistensi, dan kegagalan moral tatanan global yang ada. Tetapi ia juga menawarkan kesempatan untuk perbaikan. Setiap langkah menuju keadilan bagi Palestina adalah langkah menuju dunia yang lebih konsisten dengan prinsip-prinsip yang diklaimnya. Setiap keberhasilan dalam advokasi Palestina adalah penguatan bagi sistem internasional berbasis aturan. Setiap pengakuan terhadap hak-hak Palestina adalah penegasan bahwa hukum, bukan kekuatan, yang harus mengatur hubungan antar bangsa.
Di tengah dunia yang terbakar—dengan keretakan transatlantik, persaingan kekuatan besar, dan krisis multilateralisme—perjuangan Palestina mungkin tampak semakin sulit. Tetapi justru di saat-saat tergelap inilah kejelasan tujuan dan kecerdasan strategi menjadi paling penting. Kita harus tetap teguh pada prinsip kemerdekaan Palestina, tetapi kita juga harus cerdas dalam memilih bahasa dan taktik untuk memperjuangkannya. Kita harus berani memasuki ruang-ruang yang tidak nyaman, berbicara dalam bahasa yang mungkin asing, dan menjangkau mereka yang selama ini memusuhi. Bukan untuk mengkhianati perjuangan, tetapi untuk membuat perjuangan itu benar-benar mencapai tujuannya.
Kemerdekaan Palestina bukanlah utopia. Ia adalah hak yang dijamin oleh hukum internasional, didukung oleh ratusan resolusi PBB, dan diperjuangkan oleh generasi demi generasi. Tugas kita adalah memastikan bahwa hak itu akhirnya terwujud—bukan hanya dalam spanduk dan slogan, tetapi dalam kenyataan pahit manis di tanah Palestina yang merdeka. Untuk itu, kita harus bersedia melakukan apa pun yang diperlukan, selama tidak mengkhianati prinsip, untuk mencapai tujuan suci itu.
Merdeka!